
Perkawinan dan Kesehatan Mental dalam Konteks Publik
Perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi ketika melibatkan tokoh-tokoh publik. Ia berubah menjadi bahan perdebatan, penilaian, bahkan penghakiman. Gugatan perceraian Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil menjadi contoh bagaimana isu rumah tangga elite segera menjadi tontonan publik. Namun di balik keramaian pemberitaan dan komentar warganet, ada masalah yang lebih mendasar: kesehatan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan.

.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat peningkatan jumlah perceraian. Data dari lembaga peradilan agama menunjukkan bahwa ratusan ribu kasus perceraian diajukan setiap tahun. Mayoritas gugatan diajukan oleh perempuan dengan alasan beragam seperti konflik jangka panjang, kekerasan emosional, masalah ekonomi, hingga hilangnya komunikasi yang sehat dalam hubungan.
Ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya tentang kegagalan mempertahankan pernikahan, tetapi sering kali berkaitan dengan upaya menyelamatkan kesehatan mental. Namun, ketika perceraian terjadi pada tokoh politik atau figur publik, narasi yang muncul cenderung menyederhanakan masalah. Masyarakat terjebak pada pertanyaan dangkal: siapa yang salah, siapa yang berkhianat, dan siapa yang pantas disalahkan.
Media sosial memperparah situasi ini dengan membanjirnya opini spekulatif, analisis moral, dan komentar yang sering kali melebihi batas empati. Padahal, tidak ada individu yang kebal dari tekanan psikologis. Status sosial, jabatan, dan citra keluarga ideal tidak otomatis membuat seseorang imun dari luka batin. Justru bagi tokoh publik, beban psikologis sering kali berlipat ganda. Selain menghadapi krisis pribadi, mereka juga harus menanggung ekspektasi publik dan kehilangan ruang privat untuk pulih.
Fenomena ini berbahaya bagi kesehatan mental bangsa. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam literasi kesehatan mental. Survei nasional menunjukkan bahwa jutaan warga mengalami gejala kecemasan dan depresi, sementara akses terhadap layanan kesehatan jiwa masih terbatas dan stigma tetap kuat. Dalam konteks ini, cara masyarakat memperlakukan perceraian elite mencerminkan wajah empati sosial kita.
Alih-alih menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum edukasi—bahwa relasi yang tidak sehat dapat berdampak serius pada kesehatan jiwa—masyarakat justru menormalisasi penghakiman. Kolom komentar berubah menjadi ruang “pengadilan moral” yang tidak mengenal asas kehati-hatian. Kekerasan verbal dan emosional dianggap wajar, bahkan menghibur.
Dampaknya tidak berhenti pada figur publik. Narasi yang dibangun ikut memengaruhi masyarakat luas. Perceraian kembali diposisikan sebagai aib, bukan sebagai keputusan hidup yang kompleks. Perempuan yang menggugat cerai sering kali distigmatisasi, seolah kegagalan rumah tangga selalu menjadi tanggung jawabnya. Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan lebih berani mengajukan perceraian justru karena kesadaran akan kesehatan mental dan keselamatan diri.
Kasus Atalia dan Ridwan Kamil, apa pun latar belakang personalnya, seharusnya dibaca dalam kerangka yang lebih dewasa. Bahwa rumah tangga, bahkan yang tampak harmonis di ruang publik, tetap rentan terhadap konflik. Bahwa menjaga citra tidak selalu sejalan dengan menjaga kesehatan jiwa. Dan bahwa berpisah bisa menjadi pilihan terakhir ketika dialog dan pemulihan tidak lagi memungkinkan.
Media memiliki tanggung jawab besar dalam membingkai isu ini. Pemberitaan yang sensasional mungkin menguntungkan secara klik, tetapi miskin kontribusi sosial. Sebaliknya, jurnalisme yang berempati dapat menjadikan perceraian elite sebagai pintu masuk diskusi tentang pentingnya konseling, kesehatan mental, dan relasi yang setara.
Begitu pula publik. Simpati tidak harus diwujudkan dalam pembelaan membabi buta atau hujatan keras. Empati sejati justru hadir dalam sikap menahan diri, menghormati privasi, dan menyadari bahwa tidak semua luka layak dipertontonkan.
Perceraian elite bukan sekadar kabar selebritas politik. Ia adalah cermin kesehatan mental masyarakat kita. Cara kita meresponsnya hari ini akan menentukan apakah Indonesia bergerak menuju bangsa yang lebih matang secara emosional, atau terus terjebak dalam budaya penghakiman yang melelahkan jiwa bersama.


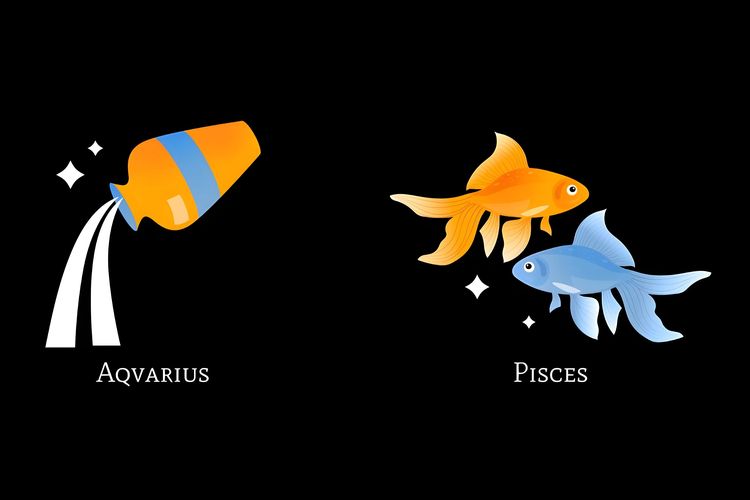









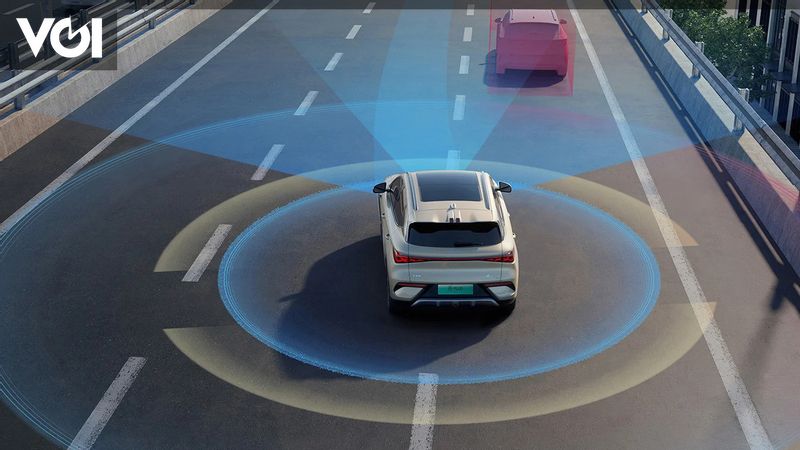

Komentar
Kirim Komentar