
Hari Kebudayaan dan Karnaval Seremonial
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Hari Kebudayaan Nasional dan merayakannya untuk pertama kali pada 16–18 Oktober 2025. Perayaan ini diisi dengan Karnaval Budaya Nusantara di kawasan Museum Benteng Vredeburg hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, menampilkan ratusan peserta dari 38 provinsi dengan busana adat, musik daerah, dan parade kendaraan hias.

.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Dalam narasi resminya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi bagian dari upaya memperkuat karakter dan kepribadian bangsa sebagaimana amanat Trisakti Bung Karno. Ia menggambarkan kebudayaan sebagai fondasi moral dan spiritual yang harus mengikat bangsa dalam keberagaman.
Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah Hari Kebudayaan benar-benar menjadi pondasi dari Trisakti Bung Karno—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—atau sekadar seremoni musiman yang hilang maknanya setelah parade usai?
Setiap tahun kita menyaksikan pola yang sama. Saat Hari Batik Nasional tiba, semua berbondong-bondong mengenakan batik dan berswafoto di media sosial. Esoknya, semuanya kembali ke pakaian kasual.
Soekarno pernah mengingatkan bahwa bangsa yang kehilangan rasa malu terhadap budayanya akan kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa merdeka.
Kita tampak seperti bangsa yang memakai simbol budaya, bukan menghayatinya—sebuah ironi yang mencerminkan rapuhnya kepribadian di balik parade seremonial.
Kebaya, Parade, dan Ironi Kepribadian
Jarang sekali perempuan Indonesia mengenakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari, kecuali pada acara resmi atau perayaan tertentu. Padahal, busana tradisional bukan hanya pakaian, tetapi manifestasi nilai, kesopanan, dan identitas nasional.
Negara lain memberi teladan. Di Bhutan, seluruh warga wajib mengenakan pakaian tradisional gho dan kira dalam kehidupan publik sesuai aturan Driglam Namzha. Di Jepang, meskipun kimono jarang dipakai harian, semangat disiplin dan estetika tradisional tetap tertanam dalam perilaku dan etos kerja mereka.
Sementara itu, di Indonesia, kebaya dan batik lebih sering muncul di panggung dan parade. Setelah acara usai, budaya tubuh yang semula “berbusana kebaya” segera berganti dengan budaya “berpakaian sesuka hati”—seolah keanggunan perempuan Indonesia hanya dipentaskan satu hari dalam setahun.
Satire sosial yang tajam muncul dalam fenomena sekelompok relawan yang melancarkan protes dengan mengenakan pakaian minim di depan Mabes Polri sebagai kritik terhadap ketidakadilan. Peristiwa ini bukan tuntutan literal untuk menghilangkan norma, melainkan kritik metaforis terhadap pergeseran nilai budaya menjadi komoditas politik dan media sosial yang mengaburkan makna sebenarnya dari budaya.
Kita hidup di zaman di mana kebudayaan lebih sering tampil di panggung daripada tumbuh di nurani.
Bung Karno dan Gagasan “Berkebudayaan dan Berkepribadian”
Dalam Pidato Kongres Kebudayaan Nasional 1951 di Yogyakarta, Bung Karno menegaskan:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berkepribadian, yang berkebudayaan sendiri. Kebudayaan tidak boleh menjadi alat meniru bangsa lain, tetapi harus menggali sumber dari tanah airnya sendiri.”
Gagasan ini menjadi dasar Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam Pidato Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945), Bung Karno kembali menegaskan:
“Kita hendak mendirikan satu negara di mana semua orang dapat menjadi dirinya sendiri, tanpa kehilangan kepribadian kebangsaannya.”
Namun kini, idealisme itu kerap memudar di tengah riuh parade dan simbolisme. Budaya direduksi menjadi pertunjukan, bukan gaya keseharian.
Wiji Thukul dan Tan Malaka: Suara dari Pinggir
Penyair Wiji Thukul dalam kumpulan puisinya Nyanyian Akar Rumput (1998) menggambarkan kebudayaan sebagai suara rakyat kecil:
“Hanya akar rumput yang bisa bernyanyi tentang penderitaan rakyat, bukan panggung-panggung megah yang menari di atasnya.”
Thukul menegaskan bahwa kebudayaan hidup di jalanan dan di hati rakyat, bukan di gedung pertunjukan pemerintah.
Sementara itu, Tan Malaka dalam Madilog (1943) menulis:
“Cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri; kemajuan datang dari logika yang berdiri atas bukti, bukan sekadar imitasi.”
Keduanya mengingatkan bahwa bangsa yang hanya meniru—baik dalam politik maupun budaya—akan kehilangan kemampuan berpikir kritis dan mencipta.
Maka, Hari Kebudayaan seharusnya menjadi refleksi nasional, apakah kita masih memiliki semangat kebudayaan yang berpikir dan berjiwa, atau hanya sisa-sisa seremoni dan nostalgia?
Hari Komedi Nasional: Tawa sebagai Wajah Budaya
Selain Hari Kebudayaan, pemerintah juga menetapkan Hari Komedi Nasional pada 27 September 2025, bertepatan dengan hari lahir Bing Slamet, ikon pelawak dan penyanyi legendaris Indonesia.
Kementerian Kebudayaan menjelaskan bahwa penetapan ini merupakan bentuk penghormatan kepada para seniman lawak Indonesia sekaligus bagian dari upaya menjaga politik kegembiraan bangsa. Dalam pandangan Menteri Fadli Zon, humor mencerminkan kedewasaan budaya: ia adalah cara bangsa menertawakan dirinya sendiri tanpa kehilangan akal sehat.
Sebagaimana Gus Dur yang dikenal menggunakan humor untuk mengkritik kekuasaan, tawa yang berbudaya adalah tawa yang menyadarkan, bukan sekadar menghibur.
“Humor adalah cara orang cerdas menegur tanpa membuat luka.” (Kutipan populer yang sering dikaitkan dengan Gus Dur dari berbagai wawancara dan esai).
Dari Parade ke Kepribadian
Peringatan Hari Kebudayaan seharusnya tidak berhenti pada parade, lomba busana, atau festival musik daerah. Ia mesti menjadi cermin kepribadian bangsa.
Budaya bukan sekadar tarian, batik, atau kebaya—tetapi cara berpikir, berbicara, dan memperlakukan sesama.
Bung Karno pernah berpesan:
“Kebudayaan Indonesia harus menggali sumber dari tanah airnya sendiri, dari rakyatnya sendiri, dan dari kepribadiannya sendiri.”
Kini waktunya kita berhenti menjadikan budaya sebagai panggung identitas, dan mulai menghidupkannya sebagai laku dalam keseharian.
Kebaya tak perlu hanya untuk acara di istana, batik tak harus menunggu hari perayaan, dan tawa tak semestinya berhenti di televisi.
Sebab bangsa yang benar-benar berbudaya bukanlah bangsa yang gemar berpesta budaya, melainkan bangsa yang menjadikan budaya sebagai gaya hidup sehari-hari.


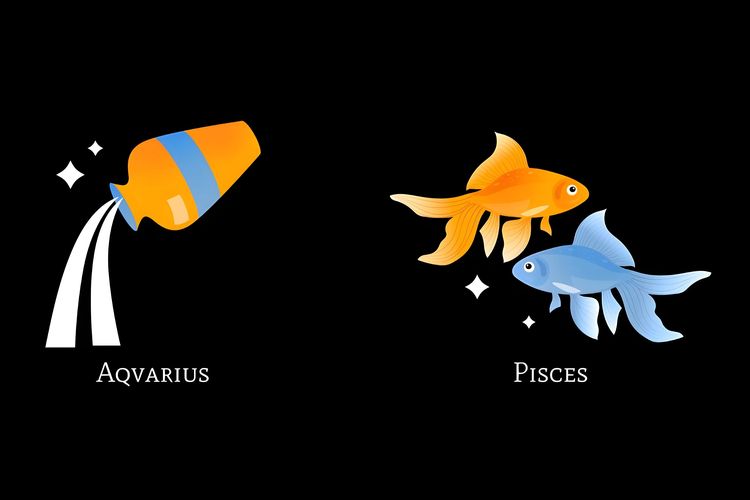









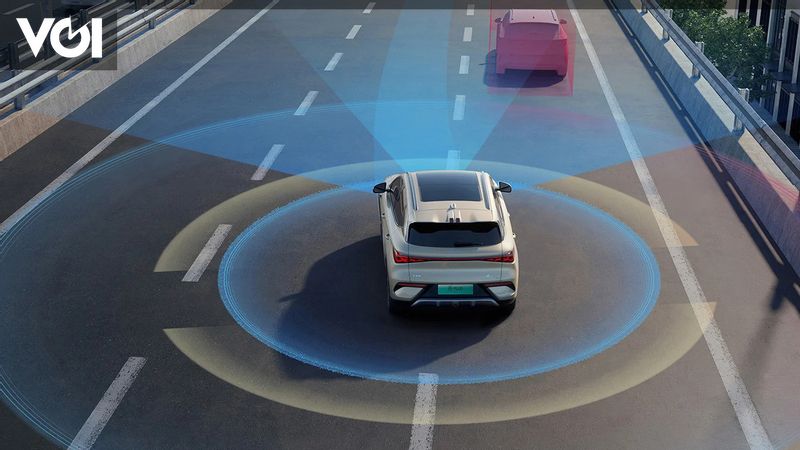

Komentar
Kirim Komentar