
Bisnis, JAKARTA — Meskipun Katolik bukanlah agama mayoritas di Jepang, jejak misionaris Katolik masih terasa di negara tersebut melalui lembaga pendidikan tinggi seperti Fuji Women’s University di Sapporo, Prefektur Hokkaido. Universitas ini merayakan 100 tahun kehadirannya pada tahun ini. Saya berkesempatan mengunjungi universitas ini pada Jumat (5/12/2025) sebagai bagian dari agenda Jenesys Exchange Program 2025 yang saya ikuti bersama belasan jurnalis lain asal Asean pada 2-9 Desember 2025 lalu.

.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Jenesys merupakan singkatan dari Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths. Program ini diinisiasi oleh Pemerintah Jepang, khususnya Kementerian Luar Negerinya untuk mempererat hubungan persahabatan dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.
Sesuai dengan namanya, universitas tersebut merupakan universitas khusus untuk mahasiswi atau pelajar wanita. Rupanya, universitas ini didirikan bermula dari keprihatinan Gereja Katolik terhadap terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan Jepang pada awal abad ke-20. Jejak awalnya dapat ditelusuri ke tahun 1920, ketika tiga suster Katolik asal Jerman, yakni Sr. M. Jeanne Berchmans Salomon, Sr. M. Xavera Lehme, dan Sr. M. Candida von der Haar, tiba di Sapporo.
Kehadiran mereka di Sapporo dilatarbelakangi oleh visi seorang imam Fransiskan asal Jerman di Sapporo, Wenseslaus Kinold, yang belakangan menjadi uskup pertama di sana. Kinold meyakini masa depan Hokkaido terletak pada pendidikan perempuan, sehingga dia mengajukan permohonan kepada Gereja di Jerman untuk mengirim pendidik. Mereka melihat kebutuhan mendesak akan lembaga pendidikan bagi perempuan di wilayah Hokkaido, yang saat itu masih tergolong daerah pinggiran dalam peta modernisasi Jepang.
“Pada masa itu, hampir tidak ada pendidikan tinggi khusus untuk perempuan di Jepang. Pendidikan perempuan masih dianggap sesuatu yang sulit dan tidak menjadi prioritas,” ujar Jeremy Redlich, Wakil Presiden Fuji Women’s University, saat memperkenalkan sejarah kampus tersebut kepada peserta Jenesys.
Langkah awal yang diambil cukup sederhana. Berdasarkan informasi historis pada website resminya, sejarah sekolah ini dimulai pada 1925. Ketiga suster tersebut mendirikan Fuji Girls’ High School, sekolah menengah khusus perempuan dengan masa belajar lima tahun. Dari sinilah cikal bakal Fuji Women’s University berkembang secara bertahap, mengikuti perubahan sistem pendidikan Jepang dan kebutuhan masyarakat.
Usai Perang Dunia II, lembaga ini bertransformasi. Pada 1947 dibuka Fuji Women’s Technical College, yang kemudian direorganisasi menjadi Fuji Women’s Junior College pada 1950. Tonggak penting terjadi pada 1961, ketika Fuji Women’s College resmi dibuka sebagai perguruan tinggi empat tahun dengan pendirian Fakultas Humaniora, yang mencakup Sastra Inggris dan Sastra Jepang.
Perkembangan kampus terus berlanjut. Pada 1992, Fuji Women’s College membuka Kampus Hanakawa, yang kemudian menjadi basis bagi studi-studi yang lebih aplikatif seperti ilmu kehidupan, nutrisi, dan kesejahteraan keluarga. Seiring waktu, lembaga ini berkembang menjadi Fuji Women’s University, lengkap dengan program pascasarjana yang dibuka pada 2002.
Memasuki abad ke-21, universitas ini terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pada 2025, bertepatan dengan usia satu abad, Fuji Women’s University merombak sejumlah nama fakultas dan program studi. Tujuannya yakni untuk menegaskan fokus pada isu well-being, kesejahteraan regional, dan lingkungan pangan. Ini merupakan isu-isu yang relevan dengan tantangan masyarakat Jepang yang menua.
UNIVERSITAS SEKULER
Meski berakar dari tradisi Katolik, Fuji Women’s University kini bersifat relatif sekuler. Jeremy mengatakan bahwa mayoritas mahasiswi dan dosennya bukan penganut Katolik. Namun, nilai-nilai dasar seperti penghormatan terhadap martabat manusia, pendidikan sebagai sarana pembebasan, dan perhatian pada kelompok rentan tetap menjadi roh institusi.
Menurutnya, hingga kini, Fuji Women’s University tetap terhubung dengan jejaring universitas Katolik di Asia dan Pasifik melalui Association of Southeast and East Asian Catholic Universities (ASEACU). Tahun depan, pertemuan jejaring tersebut dijadwalkan berlangsung di Indonesia.
“Kami adalah universitas Katolik, tetapi juga universitas perempuan. Fokus kami adalah memberdayakan perempuan agar menemukan suaranya sendiri,” kata Jeremy. Ia menilai universitas perempuan masih memiliki relevansi di Jepang, meski popularitasnya menurun seiring berkurangnya jumlah penduduk usia muda. Dia menilai fenomena serupa juga terjadi di negara lain, seperti Amerika Serikat.
Meski begitu, setelah delapan tahun mengajar di Fuji Women’s University, Jeremy justru melihat nilai yang kuat dari model pendidikan ini. Menurutnya, universitas perempuan memberi ruang yang penting bagi mahasiswi untuk memberdayakan diri, menemukan suara mereka sendiri, dan memahami siapa diri mereka.
“Saya sangat berharap universitas seperti ini akan terus bertahan di masa depan. Saya tidak yakin seperti apa masa depan universitas perempuan di Jepang, tetapi mari berharap universitas ini masih memiliki masa depan,” katanya.
Meski bersifat sekuler, di lorong-lorong sekolah ini masih terdapat beberapa simbol identitas Katolik, seperti salib, ikon, kandang natal, pohon terang, atau lukisan dan gambar orang kudus. Bahkan, universitas ini memiliki kapel Katolik di dalamnya dan sesekali diselenggarakan perayaan ekaristi.
AGAMA JEPANG
Dalam kunjungan ke universitas tersebut, saya juga sempat mengikuti kelas budaya Jepang, yang dibawakan oleh salah satu dosen di universitas tersebut, yakni Mila Tillonen. Dia berasal dari Finlandia, tetapi telah 10 tahun tinggal di Jepang dan mendalami budaya Asia Timur.
Saat itu, selain kami para delegasi jurnalis asal Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang mengikuti program Jenesys, turut hadir pula beberapa mahasiswi dari universitas tersebut. Dari penjelasan Mia, terungkap bahwa agama bukanlah menjadi topik bahasan publik yang umum di Jepang. Posisi agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pun tidak begitu kuat.
Mia mengatakan bahwa agama Shinto dan Buddha mendominasi Jepang. Berdasarkan data Badan Urusan Budaya Jepang 2023, pemeluk Shinto mencapai 48% penduduk, sedangkan Buddha 47%. Di sisi lain, Katolik dan Protestan hanya sekitar 1%, sedangkan Islam dan agama-agama lainnya 4%.
“Shinto adalah agama asli Jepang, kamu tidak akan menemukannya di tempat lain. Agama ini bersifat politeistik, jadi pada dasarnya percaya pada banyak dewa. Mereka disebut Kami dalam bahasa Jepang,” kata Mia.
Agama ini sangat berorientasi pada tempat dan praktik, dan tidak memiliki pendiri atau kitab suci yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Pusat praktiknya adalah kuil-kuil Shinto, sehingga sangat berorientasi pada tempat.
Buddhisme, di sisi lain, berasal dari Tiongkok ke Jepang, dan telah dipraktikkan sejak abad ke-6. Di Jepang, Buddhisme kemudian berkembang menjadi berbagai sekte yang memiliki doktrin dan ajaran masing-masing.
“Dibandingkan dengan Shinto, agama ini lebih seperti filsafat, semacam agama intelektual, sedangkan Shinto lebih menekankan tempat dan praktik sebagai pusat agama,” katanya.
Menariknya, lanjutnya, Badan Urusan Budaya Jepang mencatat jumlah penganut agama di Jepang mencapai 172,2 juta penduduk. Hal ini unik, sebab jumlah penduduk Jepang hanya 124,35 juta penduduk. Hal ini terjadi karena satu orang di Jepang bisa tercatat di dua organisasi keagamaan yang berbeda. Banyak orang di Jepang berpartisipasi dalam ritual dan upacara, baik Shinto maupun Buddha sekaligus. Namun, mereka mungkin tidak menganggap diri mereka religius dalam arti afiliasi atau keyakinan.
“Yang membuat hal ini semakin membingungkan adalah ketika orang Jepang ditanya tentang agama mereka, mereka biasanya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki agama,” katanya.
Menurut Mia, ketika berkaitan dengan agama Shinto dan Buddha, orang Jepang umumnya tidak memilih salah satu di antaranya secara eksklusif. Keduanya memiliki waktu dan tempat dalam kehidupan seseorang. Shinto, misalnya, berkaitan dengan peristiwa kehidupan. Ketika bayi lahir, mereka dibawa ke kuil Shinto. Ketika mereka berusia tiga, lima, dan tujuh tahun, anak-anak sering pergi ke upacara-upacara ini di kuil. Pernikahan juga sering berlangsung di kuil-kuil ini. Shinto juga memiliki banyak ritual dan festival tahunan.
Buddhisme, di sisi lain, memiliki peran tradisional dalam mengurus upacara pemakaman. Namun, banyak orang mengunjungi kuil dan tempat suci dalam konteks pariwisata.
Dalam konteks karakter budaya seperti ini, agama Katolik yang umumnya menuntut eksklusivitas penyembahan pada Satu Tuhan tidak begitu populer di Jepang. Meski begitu, masyarakat Jepang tidak begitu mempermasalahkan identitas agama sebuah institusi pendidikan ketika hendak memilih tempat belajar.
Di tengah masyarakat Jepang yang kerap mengaku “tidak beragama”, keberadaan Fuji Women’s University menjadi penanda bahwa jejak Katolik di Jepang tidak hadir dalam bentuk dominasi iman. Sebaliknya, Katolik hadir dalam bentuk kontribusi nyata di bidang pendidikan, khususnya pendidikan perempuan, yang terus bertahan selama satu abad.


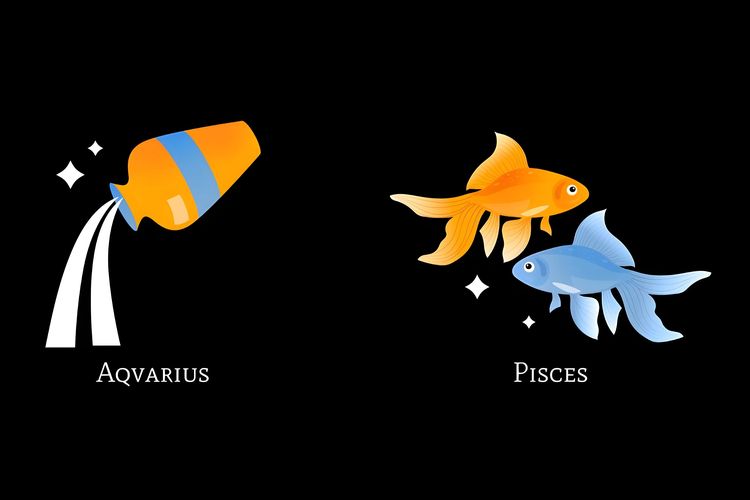









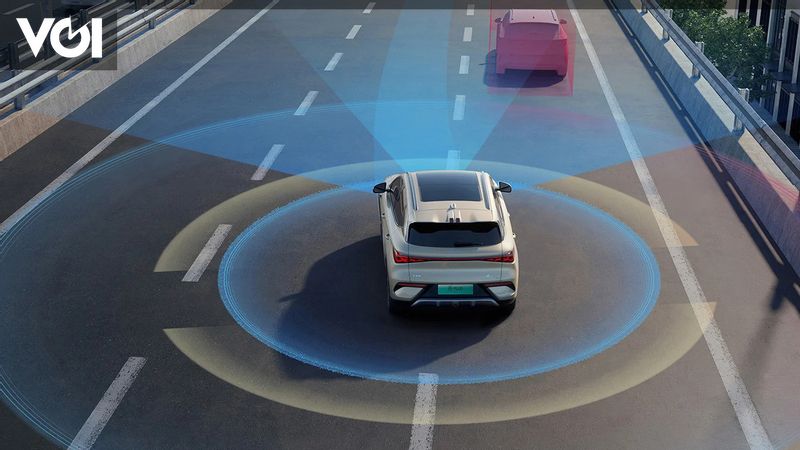

Komentar
Kirim Komentar